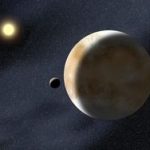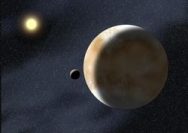INDOAKTUAL – Coba renungkan sebuah batu dilemparkan ke air yang tenang. Benturan awalnya mungkin kecil, tetapi gelombangnya menyebar jauh, mengganggu segala sesuatu yang dilaluinya. Mirip seperti itulah dampak sebuah stigma “pelakor” dimulai. Satu cap negatif, ibarat batu pertama, yang memicu rangkaian efek domino: dari sekadar sindiran, berubah menjadi stigma sosial yang meluas, lalu eskalisasi menjadi doxing, bullying, dan akhirnya pengucilan total. Dampaknya tidak hanya menghancurkan satu kehidupan, tetapi juga mengikis sendi-sendi kemanusiaan dan keadilan kita bersama.
Data dari LBH APIK (Laporan Kekerasan Siber Berbasis Gender, 2023) mengonfirmasi betapa seriusnya masalah ini: 87 kasus doxing tercatat dengan motif perselingkuhan, di mana 92% korbannya adalah perempuan yang distigma sebagai ‘pelakor’. Angka ini mungkin hanya puncak gunung es, mengingat banyak korban yang tidak melapor karena tekanan sosial.
Temuan ini sejalan dengan laporan SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) (Laporan Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia, 2023) yang mencatat peningkatan 120% kasus kekerasan siber berbasis gender selama periode 2022-2023, dengan platform media sosial menjadi episentrum penyebaran stigma dan hate speech.
Tulisan ini akan menelusuri jejak rantai kehancuran tersebut, mengungkap kedalaman dampak stigma yang selama ini kerap dipandang sebelah mata. Efek domino “pelakor” tidak berhenti pada hukuman sosial bagi yang menyandang label tersebut. Namun, akan terus menjalar, mencemari ruang publik, dan menjadi cermin kelam dari kegagalan kolektif dalam menegakkan keadilan yang setara.
Domino Pertama: Runtuhnya Kesehatan Mental dan Identitas Diri
Gelombang pertama yang menghantam adalah kehancuran kesehatan mental. Target stigma langsung dilanda kecemasan akut, serangan panik, dan depresi berat yang menyulitkannya untuk berfungsi sehari-hari. Rasa malu dan bersalah yang dipaksakan dari luar akan mengkristal, dan seringkali berubah menjadi trauma psikologis yang mendalam, mirip dengan PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder). Tubuh dan pikirannya secara terus-menerus akan berada pada mode “lawan atau lari“, tanpa memiliki tempat yang aman untuk beristirahat.
Berdasarkan penelitian Pusat Krisis Fakultas Psikologi UI (Dampak Psikologis Doxing di Media Sosial, 2023), 68% korban doxing mengalami gejala gangguan stres pasca trauma yang membutuhkan penanganan profesional. Yang lebih memprihatinkan, 40% di antaranya mengaku pernah memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup, menunjukkan betapa beratnya beban psikologis yang harus ditanggung.
Lebih menyakitkan dari sekadar rasa malu, adalah terampasnya identitas seseorang. Segala pencapaian, peran, dan kebaikannya tiba-tiba lenyap ditelan satu label, yakni: “pelakor”. Mereka tidak lagi dilihat sebagai seorang yang berdedikasi, seorang yang penyayang, atau seorang sahabat yang setia. Di mata masyarakat, eksistensi mereka direduksi hanya menjadi karikatur satu dimensi dari sebuah “kesalahan”, sehingga menghapus seluruh narasi hidupnya yang kompleks.
Dalam kondisi tekanan yang tidak tertahankan, pikiran untuk mengakhiri segala rasa sakit bisa menjadi menggoda. Beban yang dirasakan satu orang, seringkali terasa seperti beban seluruh dunia, dapat mendorong munculnya ide untuk menyakiti diri sendiri secara ekstrem sebagai satu-satunya jalan keluar. Seorang psikolog klinis, Andriana Putri, dalam wawancara eksklusif dengan Media Indonesia (2023) menyatakan, “Trauma akibat stigmatisasi massal di media sosial ini unik dan mendalam. Korban tidak hanya berduka atas hubungan yang rusak, tetapi juga harus berperang melawan persepsi publik yang memusuhinya. Penyembuhannya membutuhkan waktu yang sangat lama, karena luka itu terus diingatkan oleh dunia digital.” Temuan ini membuktikan bahwa dampak stigmatisasi melampaui sekadar kesedihan sesaat, melainkan merupakan luka psikologis jangka panjang yang secara progresif menggerogoti ketahanan mental.
Pada situasi seperti ini, kata-kata Nelson Mandela (Long Walk to Freedom, 1994) terasa sangat relevan, “Merampas kebebasan seseorang adalah merampas martabat dasarnya.” Stigmatisasi “pelakor” merupakan perampasan kebebasan dan martabat tersebut. Ia merampas kebebasan untuk move on, untuk ditegakkan haknya, dan untuk dilihat kembali sebagai manusia utuh.
Domino Kedua: Runtuhnya Kehidupan Ekonomi dan Profesional
Dampak ekonomi seringkali menjadi realitas pahit yang langsung dirasakan. Sebuah unggahan di media sosial, bisa dengan cepat berubah menjadi surat pemecatan. Perusahaan atau institusi seringkali mengambil jalan pintas dengan merilis pegawai yang tersangkut skandal, daripada menanggung risiko reputasi institusi tercoreng. Dalam sekejap, seseorang bukan hanya kehilangan sumber penghidupannya, tetapi juga dicap sebagai “liabilitas” yang tidak diinginkan di dunia profesional.
Data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Survei Praktik HR di Era Digital, 2023) menunjukkan bahwa 25% perusahaan di Indonesia mengaku pernah memecat karyawan karena alasan yang berkaitan dengan isu moralitas pribadi yang viral di media sosial. Sementara itu, survei LinkedIn (Workplace Culture Report, 2024) mengungkap bahwa 73% perekrut akan mempertimbangkan membatalkan proses rekrutmen jika menemukan konten negatif tentang kandidat di internet.
Bahkan ketika berusaha bangkit, rekam jejak digital yang terpajang di internet menjadi jerat yang nyaris tidak terlepaskan. Nama yang sudah terkait dengan skandal akan mudah ditemukan oleh calon pemberi kerja hanya dengan sekali klik di mesin pencari. Jejak digital dapat menjadi penjara yang membuat peluang untuk mendapatkan pekerjaan baru nyaris tertutup, sehingga dapat mengubur harapan untuk memulai lembaran baru.
Inilah bukti nyata bahwa hukuman sosial seringkali melampaui batas kewajaran. Seorang konselor karir, Rini Hapsari, dalam seminar ‘Workplace Mental Health’ yang diselenggarakan oleh Asosiasi Psikologi Indonesia (2023) menegaskan, “Kehilangan pekerjaan akibat stigma bukan hanya soal keuangan. Ini adalah pukulan ganda terhadap identitas dan harga diri, menciptakan rasa tidak berdaya yang mendalam dan ketakutan akan masa depan yang suram.” Menghancurkan mata pencaharian seseorang merupakan bentuk hukuman yang tidak proporsional, sebuah konsekuensi yang jauh melebihi kesalahan yang diperbuatnya.
Realitas ketidakadilan ini mengingatkan kita pada pernyataan aktivis sosial Dorothy Day (The Long Loneliness, 1952), “Tidak ada orang yang memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman yang tidak perlu.”. Menghancurkan kehidupan profesional seseorang sebagai bentuk hukuman yang tidak perlu dan kejam. Tindakan ini menunjukkan bagaimana kemarahan massa telah mengabaikan prinsip keadilan yang mendasar, yaitu hukuman haruslah memiliki batas dan proporsi.
Domino Ketiga: Runtuhnya Hubungan Personal dan Sistem Pendukung
Gelombang stigma tidak hanya menerpa individu, tetapi juga meruntuhkan seluruh hubungan personal di sekitarnya. Lingkaran pertemanan yang dulu hangat, tiba-tiba berubah menjadi sepi dan dingin. Seseorang bisa saja mendapati dirinya telah dihapus dari grup percakapan atau diabaikan dalam pertemuan. Pengucilan ini terasa seperti hukuman tambahan yang semakin mengisolasi mereka dari dunia.
Dampaknya bahkan merembet kepada keluarga inti. Orang tua dan saudara ikut menanggung beban aib yang tidak mereka ciptakan. Mereka bisa menerima sindiran, pertanyaan menyudutkan, atau bahkan penghakiman dari tetangga maupun lingkungan sosial. Rasa malu yang dipikul keluarga sering kali menciptakan dinamika rumit di rumah, yang seharusnya menjadi tempat berlindung yang aman.
Ironisnya, kehilangan “support system” terjadi justru ketika seseorang paling membutuhkan dukungan untuk bertahan. Psikolog keluarga, Bayu Waskito, dalam jurnal ‘Keluarga dan Masyarakat’ (2024) menjelaskan, “Dalam situasi krisis, dukungan sosial adalah faktor penyembuh utama. Ketika itu dicabut, kita tidak hanya menghadapi satu trauma, tetapi trauma ganda, yakni: dikhianati oleh komunitas dan ditinggalkan oleh orang-orang terdekat.” Kesendirian inilah yang memperparah luka mental, membuat pemulihan terasa hampir mustahil.
Filsuf eksistensialis Søren Kierkegaard (1843) memberikan perspektif relevan ketika menyatakan, “Kehidupan hanya dapat dipahami dengan melihat ke belakang; tetapi harus dijalani dengan melihat ke depan.”. Stigma “pelakor” memutus akses seseorang untuk ‘menjalani hidup ke depan’. Mereka terus-menerus dirantai pada satu masa lalu, dikucilkan oleh orang-orang yang seharusnya membantunya untuk bangkit dan melanjutkan hidup.
Domino Keempat: Runtuhnya Ruang Aman dan Solidaritas Antarperempuan
Yang paling memilukan dari fenomena ini adalah bagaimana stigma “pelakor” justru paling sering dihembuskan dan diperkuat oleh sesama perempuan. Komentar pedas, pelabelan negatif, dan aksi doxing justru banyak berasal dari suara-suara perempuan lain. Praktik ini melahirkan ironi sosial yang pahit, yakni: solidaritas yang seharusnya tumbuh di antara perempuan, justru tergantikan oleh budaya saling mencurigai dan menuduh.
Praktik saling menghakimi akan melahirkan budaya ketidakpercayaan yang toksik. Daripada membangun solidaritas, perempuan justru dibuat saling memandang dengan curiga. Setiap perempuan lain bisa dilihat sebagai ancaman potensial yang siap “merebut” pasangannya. Kondisi tersebut merusak potensi kekuatan kolektif perempuan dan memecah belah dari dalam.
Survei yang dilakukan oleh LSM ‘Perempuan Bergerak’ (Survei Keamanan Digital Perempuan Indonesia, 2024) terhadap 1.000 responden perempuan mengungkap fakta mencengangkan: 85% perempuan mengaku merasa tidak aman menyampaikan pendapat di ruang digital, sementara 62% pernah mengalami atau menyaksikan perempuan lain dihukum sosial oleh sesama perempuan karena dianggap melanggar norma.
Akibatnya, ruang publik, baik daring maupun luring, akan berubah menjadi medan yang berbahaya. Setiap perempuan berpotensi menjadi sasaran, menciptakan iklim ketakutan dan kompetisi tidak sehat yang konstan. Psikolog sosial, Amanda Margia, dalam diskusi panel ‘Perempuan dan Media Sosial’ yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan (2023) menjelaskan, “Ketika perempuan menjadi algojo bagi sesamanya, maka yang terbentuk adalah masyarakat yang terfragmentasi. Trauma kolektif akan mengajarkan bahwa tidak ada ruang yang benar-benar aman, bahkan di antara kelompok sendiri.”
Audre Lorde (The Uses of Anger: Women Responding to Racism, 1981), seorang penulis dan aktivis feminis, dengan tegas menyatakan, “Saya tidak bebas selama perempuan mana pun masih tidak bebas, bahkan ketika belenggunya sangat berbeda dengan milikku.”. Dengan menjatuhkan hukuman pada perempuan lain, justru memperkuat belenggu yang membatasi kebebasan semua perempuan. Solidaritas yang dipatahkan, pada akhirnya melemahkan posisi semua perempuan di masyarakat.
Domino Kelima: Runtuhnya Keadilan dan Pengaburan Akar Masalah
Efek domino yang paling berbahaya adalah pengaburan total terhadap prinsip keadilan. Stigma “pelakor” berhasil mengalihkan seluruh amarah masyarakat hanya kepada satu pihak: perempuan yang dijuluki sebagai “perebut”. Dalam narasi publik, kemarahan yang seharusnya ditujukan kepada semua pihak yang terlibat, tiba-tiba menjadi fokus yang sempit dan timpang.
Sementara perempuan menjadi sasaran utama, laki-laki yang berselingkuh sering kali lolos dari tanggung jawab setara. Masyarakat cenderung memaklumi dengan stereotip usang seperti “laki-laki memang begitu” atau “digaet, ya wajar kalau nyaut”. Ia mungkin hanya disebut “selingkuh”, sebuah label yang jauh lebih ringan dan tidak menghancurkan dibandingkan “pelakor”.
Dengan fokus yang keliru pada satu pihak, akar persoalan yang sesungguhnya (seperti: komitmen yang rapuh dan komunikasi yang tidak sehat dalam hubungan), justru terabaikan. Persoalan komitmen yang lemah, komunikasi yang buruk, atau ketidakpuasan dalam relasi primer, semuanya tertutup oleh drama stigmatisasi. Psikolog, Fajar Aditya, dalam penelitiannya yang dipublikasikan di Jurnal Psikologi Sosial (2023) menegaskan, “Dengan menjadikan ‘pelakor’ sebagai kambing hitam, pasangan terancam tidak pernah belajar dari masalah dalam hubungan mereka. Siklus yang sama bisa terulang karena akarnya tidak pernah ditangani.”
Filsuf George Orwell (1949) mengingatkan kita, “Dalam waktu penipuan universal, menyatakan kebenaran adalah tindakan revolusioner.” Pada konteks ini, kebenaran revolusionernya adalah mengakui bahwa stigma “pelakor” sebagai sebuah penipuan yang mengalihkan dari ketidakadilan gender yang nyata. Keadilan sejati menuntut pertanggungjawaban yang setara dari semua pihak, bukan hukuman selektif yang didasarkan pada bias gender.
Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian PPPA tahun 2023 mengungkap ketimpangan sistemik: dalam kurun 2020-2023, hanya 15% laporan kekerasan terhadap laki-laki yang diproses secara hukum, berbanding tajam dengan 45% ketika korbannya perempuan.
Menghentikan Rantai Domino
Dari keruntuhan kesehatan mental, kehancuran karier, retaknya hubungan personal, hingga hancurnya solidaritas dan terdistorsinya keadilan, kelima efek domino akan membentuk siklus kehancuran yang sempurna. Setiap kali kita membagikan gunjingan, atau memilih diam saat melihat ketidakadilan, maka kita secara aktif mendorong domino berikutnya untuk jatuh. Kita semua memegang potensi untuk menjadi bagian dari solusi, atau justru memperpanjang rantai masalah ini.
Perubahan dimulai dari kesadaran masing-masing. Mari hentikan penggunaan kata “pelakor” yang sarat stereotip dan mulai melihat persoalan secara kritis. Sebelum ikut menyebarkan konten yang menghakimi, tanyakan pada diri sendiri: “Dampak domino apa yang mungkin saya picu dengan satu kali klik “share” ini?” Psikolog sosial, Ratna Indriyanti, dalam konferensi pers ‘Stop Kekerasan Siber’ bersama Kementerian PPPA (2024) menambahkan, “Korban stigmatisasi massal tidak hanya butuh pemulihan diri, tapi juga pengakuan sosial bahwa yang dialaminya adalah salah. Rekonsiliasi ini penting untuk memutus siklus trauma kolektif.”
Kita juga perlu mendorong perubahan di tingkat yang lebih luas. Media dan influencer harus berhenti menjadi “pendorong domino pertama” dengan memberitakan kasus perselingkuhan secara sensasional dan tidak adil gender. Pemberitaan yang bertanggung jawab akan membantu meredam, bukan memicu, gelombang kekerasan siber.
Firman Allah dalam QS Al-Ma’idah ayat 32 mengingatkan kita, “Barangsiapa membunuh seorang manusia… maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” Pada konteks ini, menyelamatkan seorang manusia dari stigmatisasi yang menghancurkan, berarti menyelamatkan kemanusiaan kita bersama.
Rasulullah SAW juga bersabda, “Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain, dia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya terzalimi.” (HR. Bukhari). Pertanyaannya kini bukan lagi, “Apakah seseorang pantas disalahkan?”, tetapi “Apakah kita pantas menjadi algojo yang menghancurkan sebuah kehidupan secara sistematis, sementara kita diperintahkan untuk menjadi penjaga kehidupan dan persaudaraan?” Saatnya menghentikan efek domino, dan dimulai dari pilihan kita sendiri untuk tidak mendorong domino yang pertama.
Penulis: Harry Yulianto – Akademisi STIE YPUP Makassar