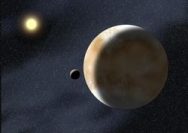INDOAKTUAL – Kemesraan terkikis, bukan oleh amarah, tetapi oleh bisik-bisik jari pada layar ponsel yang lebih didengarnya. Jempolnya asyik menyusuri umpan media sosial, sesekali tersenyum kecil pada balasan chat yang tidak pernah dibagikan. Di sebelahnya, pasangannya terlelap atau pura-pura terlelap, terbiasa dengan kehadiran fisik yang hangat, namun kedekatan emosional yang justru menjauh. Jarak satu sentimeter terasa lebih menyiksa daripada belasan kilometer; sebuah pengabaian yang disengaja dan dipilih ulang, setiap kali ujung jarinya menyentuh layar untuk menyukai kehidupan orang lain.
Di era digital, motif perselingkuhan turut berevolusi. Ia sering kali bukan lagi tentang cinta kepada orang lain, melainkan tentang upaya menyembuhkan kehampaan diri dengan mengumpulkan kekaguman dari luar. Psikolog klinis Ramani Durvasula dalam bukunya Don’t You Know Who I Am? (2020), menyebutnya sebagai upaya “menghindari perasaan hampa dalam diri sendiri”. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Andreassen et al. dalam Psychology of Popular Media Culture (2017), mengonfirmasi korelasi yang signifikan antara narsisme, kebutuhan terhadap validasi eksternal, dan perilaku mencari perhatian/pasangan di media sosial yang berpotensi terhadap ketidaksetiaan.
Tulisan ini membahas bagaimana rutinitas digital yang tampak trivial. Skrol mencari validasi, Sembunyi untuk memanipulasi, dan Hapus untuk menghindari tanggung jawab, bukan hanya kesalahan biasa. Namun, bisa berubah menjadi pola terstruktur yang mencerminkan ciri-ciri kepribadian narsistik. Melalui tiga tahap (skrol, sembunyi, hapus), artikel ini mengurai bagaimana pola narsistik mewujud dalam perselingkuhan digital. Pola ini tidak hanya mendefinisikan ulang makna ketidaksetiaan, tetapi juga menimbulkan kerusakan psikologis yang mendalam pada korbannya, menciptakan luka yang jauh lebih kompleks daripada sekadar rasa dikhianati.
Peringatan konten: artikel ini membahas topik perselingkuhan digital, pola perilaku narsistik, gaslighting, dan dampak psikologis dalam hubungan. Beberapa bagian mungkin memicu ketidaknyamanan atau kenangan yang tidak menyenangkan, terutama bagi pembaca yang pernah mengalami pengkhianatan relasional, manipulasi emosional, atau kekerasan psikologis. Disarankan untuk membaca dengan kesiapan mental dan, jika perlu, didampingi oleh pendamping atau profesional kesehatan mental. Artikel ini bertujuan untuk edukasi dan penyadaran, bukan untuk menghakimi atau menyudutkan pihak tertentu.
Pola Narsistik sebagai Alat Ego
Bagi individu berpola narsistik, aksi skrol bukanlah hiburan belaka, melainkan sebuah perburuan sistematis untuk “narcissistic supply“. Supply ini adalah bahan bakar ego mereka, berupa perhatian, kekaguman, dan validasi yang harus terus-menerus diisi ulang dari sumber eksternal. Secara psikologis, perilaku ini adalah bentuk modern dari pencarian validasi eksternal.
Perilaku ini bukan tanpa dasar psikologis. Studi yang dilakukan oleh McCain dan Campbell dalam Psychology of Popular Media Culture (2018), secara konsisten menunjukkan korelasi antara penggunaan media sosial yang intens dengan ekspresi sifat narsistik, khususnya kebutuhan akan pujian dan pengakuan. Dengan kata lain, dunia digital telah menjadi ‘pasar’ modern tempat mereka berburu ‘bahan bakar’ untuk ego yang lapar. Bagi mereka, setiap like, komentar pujian, atau percakapan mesra dengan orang baru bukan sekadar interaksi, melainkan konfirmasi vital bahwa diri mereka masih berharga, diinginkan, dan daya tariknya tetap diminati. Setiap bunyi notifikasi adalah suntikan sementara bagi harga diri yang rapuh.
Fase sembunyi kemudian mengungkap esensi manipulatif dari pola ini. Ini bukan lagi kecemasan orang yang bersalah, tetapi strategi gaslighting yang disengaja untuk mengontrol narasi dan realitas pasangan. Praktik penyembunyian ini dapat dilihat melalui lensa Communication Privacy Management Theory, di mana pelaku secara unilateral mengontrol dan melanggar aturan privasi hubungan demi mempertahankan rahasia yang menguntungkan egonya. Pada konteks narsistik, pelaku secara sepihak mengontrol batasan tersebut (menyembunyikan informasi vital dari pasangan) yang merupakan manifestasi langsung dari dinamika kekuasaan dan kontrol yang timpang dalam hubungan.
Pelaku akan menyimpan ponsel dengan cemas, menggunakan aplikasi tersembunyi, atau menghapus riwayat panggilan. Ketika diekspos, mereka dengan lihai memutar balik fakta: “Kamu yang terlalu posesif,” atau “Itu cuma bercanda, kok sensitif banget?” Tujuannya tunggal: membuat korban bingung dan meragukan penilaiannya sendiri, sehingga perburuan supply bisa tetap berlanjut.
Aksi hapus adalah puncak dari siklus ini, yang merepresentasikan penghapusan empati dan tanggung jawab. Dengan satu ketukan, bukti-bukti percakapan mesra, foto, atau janji manis lenyap, bukan hanya dari memori ponsel, tetapi juga dari akuntabilitas moral pelaku. Perilaku ini mencerminkan ketidakmampuan mendasar untuk mengakui kesalahan dan merasakan penderitaan orang lain, sebuah ciri utama narsisme. Pada konteks hukum, tindakan menghapus bukti dapat dikategorikan sebagai perusakan alat bukti, meski dalam ranah privat ini sulit dijerat. Yang paling rusak adalah fondasi kepercayaan korban. Pelaku berperilaku seolah emosi dan kenangan korban bisa di-delete semudah menghapus chat, meninggalkan korban dalam realitas yang disangkal dan rasa sakit yang dianggap tidak pernah ada.
Narsisme dalam Ritme Digital: Pola Pelanggaran Batasan
Pada intinya, pola narsisme berakar dari keyakinan keliru bahwa diri mereka istimewa dan berada di atas aturan. Kebutuhan dan keinginannya dianggap lebih penting daripada komitmen atau perasaan pasangan. Psikolog klinis Craig Malkin, dalam bukunya Rethinking Narcissism (2015), menjelaskan bahwa grandiositas sering kali adalah topeng untuk kerapuhan internal yang mendalam. Pada konteks digital, hal ini diterjemahkan menjadi hak eksklusif untuk menjalankan pola ‘skrol-sembunyi-hapus’, yaitu melanggar batasan kesetiaan secara sistematis. Mereka merasa berhak “skrol” mencari perhatian lain, karena pasangan yang ada dianggap tidak lagi cukup “hebat”. Aturan kesetiaan yang berlaku untuk orang biasa, dalam pikiran mereka, tidak relevan bagi seseorang yang spesial.
Ciri paling merusak berikutnya adalah ketiadaan empati. “Empati adalah penangkal narsisme,” menurut Ramani Durvasula (2020). Proses sembunyi dan hapus dilakukan dengan efisiensi yang dingin karena pelaku tidak benar-benar membayangkan betapa sakitnya korban menemukan pengkhianatan. Yang ada dalam pikirannya hanyalah risiko ketahuan yang mengancam citra diri, bukan hati yang hancur di seberang layar.
Rangkaian temuan penelitian konsisten menunjukkan bahwa narsisme merupakan prediktor kuat dari ketidaksetiaan. Studi meta-analisis oleh Rapp et al. dalam Personality and Social Psychology Review (2023), membahas narsisme dan dinamika hubungan, mengonfirmasi bahwa ciri ini merusak komitmen, sebagian karena defisit empati dan kepercayaan diri berlebihan.
Harga diri mereka yang rapuh bagai ‘ember bocor’, selalu membutuhkan siraman validasi tanpa henti. Satu sumber kekaguman, dari pasangan resmi, tidak akan pernah memadai. Teori dasar tentang kebutuhan narsistik berakar dari pemikiran Heinz Kohut dalam bukunya The Analysis of the Self (1971), yang menjelaskan pentingnya mirroring (‘cermin’) dan pengakuan dari lingkungan untuk perkembangan diri.
Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi istilah ‘narcissistic supply‘ dalam literatur psikoanalisis kontemporer dan di lanskap digital, memicu siklus skrol tanpa henti. Setiap like, komentar pujian, atau percakapan mesra dari orang baru adalah “supply” segar yang mengonfirmasi bahwa mereka masih dikagumi. Hubungan komitmen pun bukan lagi tujuan akhir, melainkan hanya salah satu dari banyak panggung untuk mendapatkan tepuk tangan, dan mereka merasa berhak mencari panggung lain secara diam-diam.
Dampak Psikis Selingkuh Digital Berpola Narsisme
Dampak yang diderita korban melampaui rasa sakit hati biasa; ini adalah trauma psikologis yang sistematis. Kombinasi pengkhianatan dan gaslighting, di mana realitas mereka terus-menerus disangkal, menciptakan luka yang mendalam. Korban tidak hanya berduka atas hubungan yang hancur, tetapi juga kehilangan kepercayaan fundamental terhadap penilaian dan intuisinya sendiri.
Seperti dijelaskan Robin Stern, psikolog dan penulis buku The Gaslight Effect (2007), penyangkalan realitas yang berulang merupakan taktik inti gaslighting yang secara sistematis dapat merusak kepercayaan korban terhadap persepsi dan kewarasannya sendiri. Mereka dibiarkan bertanya-tanya, “Apa aku yang berlebihan?” atau “Apa bukti-bukti ini hanya khayalanku?”, sebuah pertanyaan yang justru lebih merusak daripada fakta perselingkuhan itu sendiri.
Korban didorong untuk hidup di bawah standar yang mustahil. Karena pelaku berpola narsistik terus mencari “supply” validasi dari luar, pasangan resminya akan selalu dirasakan kekurangan. Perilaku “skrol” yang konstan mengirimkan pesan tersirat yang merendahkan: “Kamu tidak cukup menarik, tidak cukup memikat, tidak cukup baik untuk menjadi satu-satunya.” Hal ini melahirkan sindrom ketidakcukupan kronis, di mana korban merasa harus bersaing dengan fantasi dan profil-profil di dunia maya.
Dampak ini sering berujung pada gangguan kesehatan mental yang serius. Korban dapat mengalami kecemasan tinggi yang termanifestasi sebagai hypervigilance, selalu waspada dan memeriksa ponsel pasangan. Perasaan dikhianati dan diabaikan dapat memicu gejala depresi, sedangkan gaslighting yang membuat mereka ragu bercerita sering kali menyebabkan isolasi sosial yang parah. Mereka merasa terperangkap, malu, dan kehilangan ruang aman untuk berbagi, karena narasi hubungan mungkin telah dikontrol sepenuhnya oleh pelaku. Pada kasus yang berat, akumulasi trauma ini dapat memenuhi kriteria Betrayal Trauma (Trauma akibat Pengkhianatan Relasional), yang dampak psikologisnya setara dengan bentuk trauma lainnya.
Lanskap digital dengan fitur anonimitas dan rasa aman semu di balik layar, menjadi medium subur bagi pola ini. Penelitian Vital, Ben-Ze’ev, dan Karantzas dalam Computers in Human Behavior (2021) mengonfirmasi bahwa narsisme grandiose secara signifikan memprediksi kecenderungan online infidelity, yang sebagian dimediasi oleh persepsi terhadap ruang digital yang ‘terpisah’ dari realitas hubungan.
Strategi Keluar dari Jerat Narsisme Digital
Menghadapi pola yang terstruktur ini membutuhkan strategi yang sama sistematisnya, bukan dengan emosi, melainkan strategi konkret yang melindungi kewarasan.
Strategi Pertama: Kenali Pola ‘Skrol, Sembunyi, Hapus’ sebagai Sistem Perilaku, Bukan Insiden Isolasi
Langkah pertama membebaskan diri adalah mengidentifikasi pola tersebut sebagai sistem perilaku, bukan insiden terisolasi. Satu kali kesalahan mungkin dapat dimaafkan, namun rangkaian “skrol, sembunyi, hapus” yang konsisten, yang diikuti dengan penyangkalan dan pembalikan fakta, adalah tanda bahaya utama (red flag) dari dinamika manipulatif. Perilaku ini mencerminkan pola eksploitasi untuk pemenuhan ego, bukan sekadar kebodohan. Validasi terhadap pengalaman ini adalah kunci, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Schwartz et al. dalam Journal of Marital and Family Therapy (2021). Studi mereka menemukan bahwa ketika korban secara sistematis dibantu untuk mengenali pola gaslighting dan manipulasi (sering kali melalui pendampingan profesional), mereka memperoleh kerangka berpikir yang memvalidasi pengalamannya. Validasi inilah yang kemudian menjadi faktor kritis pemberdayaan untuk mengambil keputusan keluar dari hubungan yang abusive.
Strategi Kedua: Pegang Erat Realitas Anda
Untuk menghadapi gaslighting, dokumentasi menjadi senjata. Mencatat tanggal, waktu, dan bukti konkret dari perilaku yang mencurigakan, seperti screenshot pesan atau log aktivitas yang janggal. Percayalah pada insting dan kegelisahan; tubuh dan pikiran seringkali lebih dulu menangkap sinyal ketidakberesan yang coba ditutupi kata-kata manis pelaku. Seperti diungkapkan psikolog Robin Stern dalam The Gaslight Effect (2007), “Keraguan terhadap persepsi sendiri adalah tanda pertama bahwa gaslighting sedang bekerja.” Oleh karena itu, mencatat dan mempercayai bukti menjadi benteng pertahanan yang krusial.
Strategi Ketiga: Tetapkan Batasan Tegas dan Hindari Drama
Kunci menghadapi pola narsistik adalah keluar dari arena debatnya. Jangan terjebak dalam argumen berputar yang berfokus pada menyalahkan (“Kamu paranoid“) atau merasionalisasi tindakan mereka (“Semua orang juga melakukannya“). Fokuslah terhadap fakta perilaku dan batasan pribadi, dengan menggunakan pernyataan tegas: “Saya tidak nyaman dengan pesan tersembunyi ini, dan saya perlu transparansi untuk melanjutkan hubungan.” Jika mereka mengabaikan atau menyerang balik, itulah konfirmasi bahwa ada batasan yang tidak dihormati, bukan kegagalan dalam berkomunikasi.
Strategi Keempat: Cari Dukungan Eksternal
Isolasi adalah alat kontrol yang ampuh. Lawan dengan cara proaktif mencari validasi dari luar. Berbicara dengan teman atau keluarga yang netral dan tepercaya. Lebih krusial lagi, mempertimbangkan berkonsultasi dengan konselor atau psikolog profesional yang memahami dinamika kekerasan psikologis dan gangguan kepribadian narsistik. Dukungan profesional tidak hanya membantu memulihkan realitas, tetapi juga memberikan strategi coping yang sehat. Pada konteks hukum, meskipun sulit, pengumpulan bukti dan keterangan dari pihak ketiga (seperti terapis) dapat dipertimbangkan dalam proses perceraian atau gugatan, terutama yang mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum yang menyebabkan penderitaan psikis.
Dari Panggung Ego-nya, Menuju Panggung Hidup Anda
Rangkaian “Skrol, Sembunyi, Hapus” pada konteks ini telah terbukti bukan insiden biasa, namun strategi manipulasi terstruktur yang digerakkan oleh logika narsistik murni: mengontrol narasi hubungan, memanipulasi realitas korban, dan mengorbankan kesejahteraan pasangan demi suplai ego yang tidak pernah puas. Setiap tahapannya (dari perburuan validasi, penyembunyian dengan gaslighting, hingga penghapusan tanggung jawab), bekerja sinergis menciptakan sebuah sistem eksploitasi psikologis. Pola ‘skrol, sembunyi, hapus’ dengan jelas menunjukkan bahwa inti persoalannya bukanlah teknologi, melainkan karakter narsistik yang memanfaatkannya dalam pola terstruktur sebagai alat kekuasaan dan pemuas diri.
Pemahaman mendalam terhadap pola ini adalah senjata pembebasan. Ia menggeser pertanyaan menyakitkan dari “Apa kekuranganku?” menjadi “Apa yang salah dengan perilakunya?”. Ramani Durvasula (2020), psikolog klinis yang khusus menangani narsisme, menekankan bahwa ‘Pemulihan dimulai ketika Anda menyadari bahwa Anda bukanlah sumber masalahnya’. Langkah pertama yang paling krusial adalah memberi nama tepat pada dinamika ‘beracun’ (mengidentifikasinya sebagai digital infidelity berpola narsisme), dan dengan sadar memilih untuk berhenti menjadi peserta dalam permainan yang dirancang untuk kalah.
Pemahaman terhadap pola ini membawa kita pada satu kesadaran kunci: pola ‘skrol, sembunyi, hapus’ tidak hanya menggambarkan tindakan digital, tetapi lebih merupakan ekspresi dari narsisme yang merusak fondasi hubungan. Kebebasan dimulai dengan penolakan yang radikal, yakni: berhenti menjadi ‘generator’ bagi ego orang lain yang haus daya. Ini adalah keputusan untuk mematikan notifikasi dari drama hidupnya, mengambil alih kendali narasi hidup Anda, dan menjadi penjaga tunggal martabat Anda sendiri. Pada akhirnya, panggung sepenuhnya kembali menjadi milik Anda.
Penulis: Harry Yulianto – Akademisi STIE YPUP Makassar