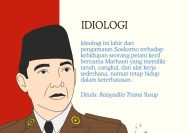Setelah lebih dari lima dekade sejak Revolusi Hijau pertama mengguncang dunia pertanian Indonesia, kini kita kembali dihadapkan pada tantangan besar, bagaimana menjadikan pertanian bukan sekadar sumber pangan, tetapi juga sumber kesejahteraan. Revolusi Hijau pertama telah membawa bangsa ini mencapai swasembada beras melalui penggunaan pupuk kimia, pestisida, dan varietas unggul. Namun, keberhasilan tersebut kini mulai menunjukkan batasnya. Lahan menjadi jenuh, petani masih berada di posisi lemah dalam rantai nilai, dan hasil pertanian sebagian besar masih dijual dalam bentuk mentah. Sudah saatnya Indonesia memulai Revolusi Hijau Kedua, di mana fokusnya bukan lagi pada seberapa banyak yang kita tanam, melainkan seberapa besar nilai yang bisa kita hasilkan dari hasil bumi itu sendiri dan di sinilah agroindustri memegang peranan kunci.
Agroindustri bukan sekadar proses mengolah hasil pertanian, tetapi sebuah sistem yang menghubungkan sektor pertanian dengan dunia industri dan pasar modern. Dalam konteks Revolusi Hijau Kedua, agroindustri menjadi penggerak utama yang mampu mengubah paradigma pertanian tradisional menuju pertanian bernilai tambah. Jika Revolusi Hijau pertama digerakkan oleh benih dan pupuk,
maka Revolusi Hijau Kedua digerakkan oleh inovasi, teknologi, dan kreativitas pengolahan hasil pertanian. Melalui pendekatan ini, petani tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga bagian dari rantai industri yang menghasilkan produk siap konsumsi dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

Peran agroindustri dalam pembangunan pertanian Indonesia sangatlah strategis. Dengan mengolah hasil panen menjadi produk olahan, petani dapat memperoleh pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Misalnya, singkong yang diolah menjadi tepung mocaf, cabai menjadi sambal kemasan, atau susu menjadi yogurt dan keju lokal. Semua ini memperpanjang rantai nilai (value chain) sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan. Agroindustri juga mampu mengurangi ketimpangan antara wilayah kota dan desa, karena proses produksi dan pengolahan bisa dilakukan langsung di daerah asal bahan baku. Dampaknya bukan hanya pada ekonomi, tetapi juga pada sosial: petani menjadi lebih mandiri, inovatif, dan memiliki posisi tawar yang lebih kuat di pasar.
Membangun Revolusi Hijau Kedua tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkannya. Keterbatasan akses terhadap teknologi pascapanen, permodalan, dan pelatihan menjadi hambatan utama bagi banyak pelaku usaha kecil di sektor pertanian. Selain
itu, sinergi antara petani, akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah masih belum optimal. Tanpa dukungan kebijakan yang berpihak seperti penyediaan infrastruktur pengolahan, pelatihan kewirausahaan, dan akses pasar digitalagroindustri sulit berkembang secara luas. Meski begitu, peluangnya sangat besar. Tren masyarakat terhadap produk lokal, pangan sehat, dan keberlanjutan menjadi momentum yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi agroindustri nasional.
Penulis: Asyifa Septia Nur Ramdiah – Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa